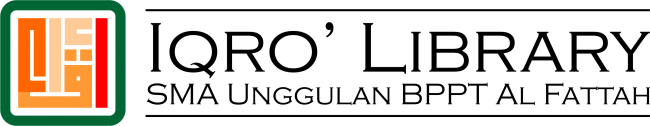Oleh : Jadid Al Farisy, S.Pd
Dalam kerata basa sastra Jawa, sebutan guru mempunyai arti digugu lan ditiru. Dua kata yang sederhana namun mengandung makna yang sangat dalam. Arti tekstual dari digugu adalah dipercaya, ditaati, atau dituruti. Sedangkan ditiru, berarti yang dicontoh atau dijadikan teladan. Dari kedua kata tersebut, sudah begitu gamblang menjelaskan secara esensi bagaimana seharusnya menjadi seorang guru itu.
Begitu mendalamnya pemaknaan terhadap seorang guru dalam lingkup pemahaman masyarakat Jawa. Seseorang yang menjadi subjek untuk ditaati dan diteladani tentu saja bukan orang yang sembarangan. Ia harus benar-benar secara dhohir dan batin mempunyai daya linuwih untuk pantas dijadikan panutan. Daya linuwih di sini bisa berarti ilmunya yang nyegara dan juga akhlaknya yang mulia.
Pada hakikatnya, untuk menjadi seorang guru tidaklah mudah seperti menjalani profesi dan pekerjaan yang lain. Seorang guru terlebih dahulu dituntut untuk bisa menjadi guru bagi dirinya sendiri sebelum menjadi guru untuk orang lain.
Ia harus bisa menyetel hati, ucapan, dan perilaku dirinya lebih dahulu sebelum mendidik akhlak para muridnya. Apa yang diperintahkan pada muridnya haruslah benar-benar ia telah lebih dulu mengamalkannya.
Seorang guru dalam prosesnya tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun juga harus bisa mendidik dan membimbing sang murid agar mempunyai budi pekerti yang luhur. Kedua fungsi inilah yang merupakan pengejahwantahan dari makna yang tersirat dalam kata guru, digugu kealiman ilmunya, dan ditiru kewira’ian akhlaqnya.
Jika berbicara tentang guru, maka tidak sekadar tentang profesi dan status sosial di masyarakat. Lebih dari itu, sejatinya menjadi guru adalah kewajiban ruhaniyah semua. Apalagi orang yang mempunyai ilmu, maka wajib untuk mengamalkan dengan menyampaikannya pada orang lain. Jangan sampai ilmu yang dimiliki hanya seperti pohon yang tidak berbuah.
Seperti yang disebutkan dalam maqolah Arab, al ‘ilmu bila amalin, kassajari bila tsamarin. Pemahaman ini mengisyaratkan bahwa semua orang pun bisa menjadi dan dianggap sebagai guru, baik bagi diri, keluarga maupun masyarakat sekitarnya.
Idealnya, seorang guru harus bisa meneladani Nabi Muhammad SAW melalui sifat kerosulan beliau. Adapun sifat-sifat wajib yang ada dalam diri Rosul adalah Shidiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah. Jika tidak bisa meneladani secara sempurna, paling tidak keempat sifat tersebut harus menjadi ruh yang melambari niat dan acuan segala ucapan dan tindak laku kita sebagai seorang guru.
Sifat yang pertama adalah shidiq yang berarti jujur. Seorang guru harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Saat-saat ini, tampaknya nilai kejujuran sudah tidak begitu diutamakan. Tidak bermaksud merendahkan, nyatanya saat ini banyak sekali kaum terpelajar yang tergolong cerdik cendekia, namun potensi kepandaiannya itu digunakan menjadi senjata untuk merugikan orang lain.
Dalam masyarakat jawa biasanya disebut dengan idiom pinter nanging gawe minteri. Seorang guru yang menggenggam nilai kejujuran dalam ucapan, hati, dan perilakunya, ia bagaikan pelita yang menerangi jiwa anak didiknya.
Guru ibarat sebuah kendhi yang berisi air. Jika dalamnya kendhi serta airnya bersih, maka yang dialirkan ke gelas, cangkir, dan wadah-wadah yang lain tentunya juga akan bersih.
Selanjutnya sifat rosul yang kedua, yaitu amanah atau dapat dipercaya. Seorang guru yang amanah pastilah ia akan bersungguh-sungguh dari hati untuk melaksanakan setiap tugas yang diembannya.
Seorang guru dituntut untuk blakasutha, apa adanya, dan selalu mengedepankan kesungguhan dalam pengabdiannya. Jika sedikit saja sikap tidak amanah itu menghinggapi diri seorang guru, maka bagaimana bisa menjamin anak didiknya yang notabene adalah seorang generasi penerus bangsa bisa akan ngugemi kesungguhan? Jika seorang pendidik saja sudah akrab dengan istilah khianat, bagaimana dengan keadaan anak-anak yang berada dalam didikannya?
Pada sifat tabligh, seorang guru harus bisa menyampaikan semua ilmunya pada anak didiknya tanpa harus ada yang disembunyikan. Terkait macam-macam personal guru perihal cara menyampaikan ilmu, penulis pernah mendengar sebuah lelucon tapi juga bisa untuk diambil pelajaran. Bahwa seorang guru dalam lembaga pendidikan tidaklah sama dengan guru dalam dunia persilatan.
Seorang guru dalam dunia pendidikan akan memberikan semua ilmu yang ia punya pada muridnya. Ia pun akan merasa sangat bangga dan bahagia jika ada anak didiknya yang bisa melebihinya dalam hal keilmuan maupun pengetahuan.
Lain halnya dengan guru dalam perguruan silat, meskipun semua ilmu kanuragan telah ia turunkan ke muridnya, namun tetap ia masih menyimpan satu ilmu pamungkas yang suatu saat bisa diandalkannya, misalnya dalam keadaan genting ketika sang murid asuhannya ada yang berkhianat dan memusuhinya. Begitulah yang sering diceritakan dalam film-film dunia persilatan.
Selanjutnya pada sifat fathonah yang berarti cerdas. Seorang guru haruslah mempunyai berbagai macam kecerdasan. Cerdas di sini tidak berarti hanya dalam ranah IQ (Intelligence quotient) saja, namun juga termasuk EQ (emotional quotient) dan SQ (spiritual quotient).
Dalam proses transfer ilmu pengetahuan, IQ mutlak dibutuhkan. Namun sebagai pendidik, seorang guru harus membekali dirinya dengan kecerdasan emosional agar mampu dengan mudah berkomunikasi dan memahami anak didiknya. Sedangkan seorang guru yang menguasai kecerdasan spiritual, ia akan dengan mudah melambari semua pengabdian dan perjuangannya lillahi ta’ala.
Jika sudah demikian, maka semua aktifitas, baik proses transfer ilmu pengetahuan maupun mendidik akan berada dalam lingkar ikhtiar dhohir dan batin. Usaha untuk menjadikan anak didiknya sukses sejatinya tidak hanya berkutat pada proses pembelajaran saja, tetapi harus diiringi juga dengan tirakat dari guru tersebut dengan mendo’akan sang murid tiada putus.
Tugas yang diemban seorang guru sungguh amatlah berat. Karena guru adalah orang tua kedua bagi para murid, ia juga harus bertanggung jawab baik secara keilmuan, sikap dan perilaku yang telah diajarkan pada anak-anaknya.
Tanggung jawab tersebut tidak hanya berakhir ketika sang anak sudah lulus sekolah. Karena secara batin, sanad keilmuan itu akan terus ada antara sang guru dengan anak muridnya. Bahkan sanad keilmuan tersebut masih tersambung hingga pada keilmuan gurunya guru tersebut hingga terus ke atas.
Hal inilah yang kemudian bisa menjadi sebab berkah dan manfaatnya ilmu yang dimiliki sang murid dikemudian hari, tentunya dengan prasyarat sang murid tetap menjaga ketawadhuannya pada gurunya. Karena sampai kapanpun, hubungan seorang guru dan murid tidak pernah mengenal kata bekas atau mantan.
* Penulis adalah Guru Bahasa Jawa dan Kepala Iqro’ Library SMA Unggulan BPPT Al Fattah Lamongan